KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Mei 05, 2014
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (disingkat Babel) adalah
sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau
utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta
pulau-pulau kecil seperti P. Lepar, P. Pongok, P. Mendanau dan P. Selat Nasik,
total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50
pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat
dengan Provinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah
penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu kota
provinsi ini ialah Pangkalpinang. Pemerintahan provinsi ini disahkan pada
tanggal 9 Februari 2001. Setelah dilantiknya Pj. Gubernur yakni H.
Amur Muchasim, SH (mantan Sekjen Depdagri) yang menandai dimulainya aktivitas
roda pemerintahan provinsi.
Selat
Bangka memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Bangka, sedangkan
Selat Gaspar memisahkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Di bagian
utara provinsi ini terdapat Laut Cina Selatan, bagian selatan
adalah Laut Jawa dan Pulau Kalimantan di bagian timur yang
dipisahkan dari Pulau Belitung oleh Selat Karimata.
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya adalah bagian dari Sumatera Selatan,
namun menjadi provinsi sendiri bersamaBanten dan Gorontalo pada
tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari Kabupaten
Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan
pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka
Tengah,Bangka Selatan dan Belitung Timur. Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatera Selatan.
Sosial Budaya
Penduduk
Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut, dalam
perjalanan sejarah yang panjang membentuk proses kulturisasi dan akulturasi.
Orang-orang laut itu sendiri berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari
Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Malaka. Sementara mereka yang
sudah berasimilasi menyebar ke seluruh Tanah Semenanjung dan pulau-pulau di
Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan
mereka yang tinggal di Riau Kepulauan berlayar ke Bangka. Datang juga
kelompok-kelompok Orang Laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang
berikutnya, ketika mulai dikenal adanya Suku Bugis, mereka datang dan menetap
di Bangka, Belitung dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan yang
Melayu, campuran Melayu-Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam proses
akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa,
Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu
melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru: Orang Melayu Bangka Belitung.
Bahasa
yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah
Bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah, namun seiring dengan
keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa
Mandarin dan bahasa Jawa.
Penduduk
Kepulauan Bangka Belitung merupakan masyarakat yang beragama dan menjunjung
tinggi kerukunan beragama. Ditinjau dari agama yang dianut terlihat bahwa penduduk
provinsi ini memeluk agama Islam dengan presentase sebesar 86.91 persen, untuk
penduduk yang menganut agama Budha sebesar 7.83 persen, agama Kristen Protestan
sebesar 2.70 persen, agama Katholik sebesar 2.45 persen dan lainnya atau 0.11
menganut agama Hindu. Tempat peribadatan agama di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung ada sebanyak 718 mesjid, 438 mushola, 102 langgar, 87 gereja
protestan, 30 gereja katholik, 48 vihara dan 11 centiya.
Budaya
dan Seni
Rumah
adat
Rumah
Panggung
Secara
umum arsitektur di Kepulauan Bangka Belitung berciri Arsitektur Melayu seperti
yang ditemukan di daerah-daerah sepanjang pesisir Sumatera dan Malaka.
Di
daerah ini dikenal ada tiga tipe yaitu Arsitektur Melayu Awal, Melayu Bubung
Panjang dan Melayu Bubung Limas. Rumah Melayu Awal berupa rumah panggung kayu
dengan material seperti kayu, bambu, rotan, akar pohon, daun-daun atau
alang-alang yang tumbuh dan mudah diperoleh di sekitar pemukiman.
Bangunan
Melayu Awal ini beratap tinggi di mana sebagian atapnya miring, memiliki
beranda di muka, serta bukaan banyak yang berfungsi sebagai fentilasi. Rumah
Melayu awal terdiri atas rumah ibu dan rumah dapur yang berdiri di atas tiang
rumah yang ditanam dalam tanah.
Berkaitan
dengan tiang, masyarakat Kepulauan Bangka Belitung mengenal falsafah 9 tiang.
Bangunan didirikan di atas 9 buah tiang, dengan tiang utama berada di tengah
dan didirikan pertama kali. Atap ditutup dengan daun rumbia. Dindingnya
biasanya dibuat dari pelepah/kulit kayu atau buluh (bambu). Rumah Melayu Bubung
Panjang biasanya karena ada penambahan bangunan di sisi bangunan yang ada
sebelumnya, sedangkan Bubung Limas karena pengaruh dari Palembang. Sebagian
dari atap sisi bangunan dengan arsitektur ini terpancung. Selain pengaruh
arsitektur Melayu ditemukan pula pengaruh arsitektur non-Melayu seperti
terlihat dari bentuk Rumah Panjang yang pada umumnya didiami oleh warga
keturunan Tionghoa. Pengaruh non-Melayu lain datang dari arsitektur kolonial,
terutama tampak pada tangga batu dengan bentuk lengkung.
Rumah
Limas
Kabupaten
Bangka sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Propinsi Kepulauan Bangka
Belitung memiliki berbagai macam potensi yang cukup menarik baik alam maupun
seni budayanya. Salah satu potensi yang menarik perhatian dan menjadi ciri
bangka belitung adalah bentuk rumah asli dengan atap berbentuk limas dan
bertangga sehingga disebut rumah panggung limas. tidak hanya bagi daerah dengan
semboyan sepintu sedulang ini namun juga bagi propinsi kepulauan bangkabelitun
 Secara umum arsitektur di Kepulauan Bangka Belitung
berciri Arsitektur Melayu seperti yang ditemukan di daerah-daerah sepanjang
pesisir Sumatera dan Malaka. Di daerah ini dikenal ada tiga tipe yaitu
Arsitektur Melayu Awal, Melayu Bubung Panjang dan Melayu Bubung Limas. Rumah
Melayu Awal berupa rumah panggung kayu dengan material seperti kayu, bambu,
rotan, akar pohon, daun-daun atau alang-alang yang tumbuh dan mudah diperoleh
di sekitar pemukiman.
Secara umum arsitektur di Kepulauan Bangka Belitung
berciri Arsitektur Melayu seperti yang ditemukan di daerah-daerah sepanjang
pesisir Sumatera dan Malaka. Di daerah ini dikenal ada tiga tipe yaitu
Arsitektur Melayu Awal, Melayu Bubung Panjang dan Melayu Bubung Limas. Rumah
Melayu Awal berupa rumah panggung kayu dengan material seperti kayu, bambu,
rotan, akar pohon, daun-daun atau alang-alang yang tumbuh dan mudah diperoleh
di sekitar pemukiman.
Bangunan
Melayu Awal ini beratap tinggi di mana sebagian atapnya miring, memiliki
beranda di muka, serta bukaan banyak yang berfungsi sebagai fentilasi. Rumah
Melayu awal terdiri atas rumah ibu dan rumah dapur, yang berdiri di atas tiang
rumah yang ditanam dalam tanah.
Berkaitan
dengan tiang, masyarakat Kepulauan Bangka Belitung mengenal falsafah 9 tiang.
Bangunan didirikan di atas 9 buah tiang, dengan tiang utama berada di tengah
dan didirikan pertama kali. Atap ditutup dengan daun rumbia. Dindingnya
biasanya dibuat dari pelepah/kulit kayu atau buluh (bambu). Rumah Melayu Bubung
Panjang biasanya karena ada penambahan bangunan di sisi bangunan yang ada
sebelumnya, sedangkan Bubung Limas karena pengaruh dari Palembang. Sebagian
dari atap sisi bangunan dengan arsitektur ini terpancung. Selain pengaruh
arsitektur Melayu ditemukan pula pengaruh arsitektur non-Melayu seperti
terlihat dari bentuk Rumah Panjang yang pada umumnya didiami oleh warga
keturunan Tionghoa. Pengaruh non-Melayu lain datang dari arsitektur kolonial,
terutama tampak pada tangga batu dengan bentuk lengkung.
Rumah
Rakit
Atraksi/Event
Budaya
Perang
Ketupat
Pagi
harinya, seusai tari serimbang digelar, dukun darat dan dukun laut bersatu
merapal mantra di depan wadah yang berisi 40 ketupat. Mereka juga berdoa kepada
Yang Maha Kuasa agar perayaan tersebut dilindungi, jauh dari bencana.
Di
tengah membaca mantra, dukun darat tiba-tiba tak sadarkan diri (trance) dan
terjatuh. Dukun laut menolongnya dengan membaca beberapa mantra, dan akhirnya
dukun darat pun sadar dalam hitungan detik.
Menurut
beberapa orang tua di tempat tersebut, ketika itu dukun darat sedang berhubungan
dengan arwah para leluhur. Kenyataannya, setelah siuman, dukun darat
menyampaikan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan (pantangan) warga selama
tiga hari, antara lain melaut, bertengkar, menjuntai kaki dari sampan ke laut,
menjemur pakaian di pagar, dan mencuci kelambu serta cincin di sungai atau
laut.
Setelah
semua ritual doa selesai, kedua dukun itu langsung menata ketupat di atas
sehelai tikar pandan. Sepuluh ketupat menghadap ke sisi darat dan sepuluh
lainnya ke sisi laut. Kemudian, 20 pemuda yang menjadi peserta perang ketupat
juga berhadapan dalam dua kelompok, menghadap ke laut dan ke darat.
Dukun
darat memberi contoh dengan melemparkan ketupat ke punggung dukun laut dan
kemudian dibalas, tetapi ketupat tidak boleh dilemparkan ke arah kepala.
Kemudian, dengan aba-aba peluit dari dukun laut, perang ketupat pun dimulai.
Ke-20 pemuda langsung menghambur ke tengah dan
saling melemparkan ketupat ke arah lawan mereka. Semua bersemangat melemparkan
ketupat sekeras-kerasnya dan berebut ketupat yang jatuh. Keadaan kacau sampai
dukun laut meniup peluitnya tanda usai perang dan mereka pun berjabat tangan.
 Selanjutnya,
perang babak kedua dimulai. Prosesnya sama dengan yang pertama, tetapi pesertanya
diganti. Perang kali ini pun tidak kalah serunya karena semua peserta melempar
ketupat dengan penuh emosi. Rangkaian upacara itu ditutup dengan upacara
Nganyot Perae atau menghanyutkan perahu mainan dari kayu ke laut. Upacara itu
dimaksudkan mengantar para makhluk halus pulang agar tidak mengganggu
masyarakat Tempilang.
Selanjutnya,
perang babak kedua dimulai. Prosesnya sama dengan yang pertama, tetapi pesertanya
diganti. Perang kali ini pun tidak kalah serunya karena semua peserta melempar
ketupat dengan penuh emosi. Rangkaian upacara itu ditutup dengan upacara
Nganyot Perae atau menghanyutkan perahu mainan dari kayu ke laut. Upacara itu
dimaksudkan mengantar para makhluk halus pulang agar tidak mengganggu
masyarakat Tempilang.
Buang
Jong
Buang
Jong merupakan salah satu upacara tradisional yang secara turun-temurun
dilakukan oleh masyarakat suku Sawang di Pulau Belitung. Suku Sawang adalah
suku pelaut yang dulunya, selama ratusan tahun, menetap di lautan. Baru pada
tahun 1985 suku Sawang menetap di daratan, dan hanya melaut jika ingin mencari
hasil laut. Buang Jong dapat berarti membuang atau melepaskan perahu kecil
(Jong) yang di dalamnya berisi sesajian dan ancak (replika kerangka
rumah-rumahan yang melambangkan tempat tinggal). Tradisi Buang Jong biasanya
dilakukan menjelang angin musim barat berhembus, yakni antara bulan
Agustus-November. Pada bulan-bulan tersebut, angin dan ombak laut sangat ganas
dan mengerikan. Gejala alam ini seakan mengingatkan masyarakat suku Sawang
bahwa sudah waktunya untuk mengadakan persembahan kepada penguasa laut melalui
upacara Buang Jong. Upacara ini sendiri bertujuan untuk memohon perlindungan
agar terhindar dari bencana yang mungkin dapat menimpa mereka selama mengarungi
lautan untuk menangkap ikan. Keseluruhan proses ritual Buang Jong dapat memakan
waktu hingga dua hari dua malam. Upacara ini sendiri diakhiri dengan melarung
miniatur kapal bersama berbagai macam sesaji ke laut. Pascapelarungan,
masyarakat suku Sawang dilarang untuk mengarungi lautan hingga tiga hari ke
depan.
.JPG) Buang
Jong dimulai dengan menggelar Berasik, yakni prosesi menghubungi atau
mengundang mahkluk halus melalui pembacaan doa, yang dipimpin oleh pemuka adat
suku Sawang. Pada saat prosesi Berasikberlangsung, akan tampak gejala
perubahan alam, seperti angin yang bertiup kencang ataupun gelombang laut yang
tiba-tiba begitu deras.
Buang
Jong dimulai dengan menggelar Berasik, yakni prosesi menghubungi atau
mengundang mahkluk halus melalui pembacaan doa, yang dipimpin oleh pemuka adat
suku Sawang. Pada saat prosesi Berasikberlangsung, akan tampak gejala
perubahan alam, seperti angin yang bertiup kencang ataupun gelombang laut yang
tiba-tiba begitu deras.
Usai
ritual Berasik, upacara Buang Jong dilanjutkan dengan Tarian
Ancak yang dilakukan di hutan. Pada tarian ini, seorang pemuda akan
menggoyang-goyangkan replika kerangka rumah yang telah dihiasi dengan daun
kelapa, ke empat arah mata angin. Tarian yang diiringi dengan suara gendang
berpadu gong ini, dimaksudkan untuk mengundang para roh halus, terutama roh
para penguasa lautan, untuk ikut bergabung dalam ritual Buang Jong. Tarian
Ancak berakhir ketika si penari kesurupan dan memanjat tiang tinggi yang
disebut jitun. Selain Tarian Ancak, Tari Sambang Tali juga
dijadikan salah satu rangkaian acara dalam upacara Buang Jong. Tarian yang
dimainkan oleh sekelompok pria ini, diambil dari nama burung yang biasa menunjukkan
lokasi tempat banyaknya ikan buruan bagi para nelayan di laut. Ketika nelayan
hilang arah, burung ini pula yang menunjukkan jalan pulang menuju
daratan.Upacara Buang Jong kemudian dilanjutkan dengan ritual Numbak
Duyung, yakni mengikatkan tali pada sebuah pangkal tombak, seraya
dibacakan mantra. Mata tombak yang sudah dimantrai ini sangat tajam, hingga
konon dapat digunakan untuk membunuh ikan duyung. Karena itu pula ritual ini
disebut dengan Numbak Duyung. Ritual kemudian dilanjutkan dengan
memancing ikan di laut. Konon, jika ikan yang didapat banyak, maka orang yang
mendapat ikan tersebut tidak diperbolehkan untuk mencuci tangan di laut.Setelah
itu, Buang Jong dilanjutkan dengan acara jual-beli jong. Pada acara ini, orang
darat (penduduk sekitar perkampungan suku Sawang) turut dilibatkan. Karena,
jual beli di sini tidak dilakukan dengan menggunakan uang, namun lebih kepada
pertukaran barang antara orang darat dengan orang laut. Pada acara ini, dapat
terlihat bagaimana orang darat dan orang laut saling mendukung dan menjalin
kerukunan. Dengan perantara dukun, orang darat meminta agar orang laut mendapat
banyak rejeki, sementara orang laut meminta agar tidak dimusuhi saat berada di
darat. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan Beluncong, yakni menyanyikan
lagu-lagu khas suku Sawang dengan bantuan alat musik sederhana.
Usai Beluncong, acara disambung dengan Nyalui, yaitu mengenang
arwah orang-orang yang sudah meninggal melalui nyanyian.
Mandi
Belimau
 Mandi
Belimau adalah salah satu adat istiadat di Pulau Bangka Belitung yang diadakan
menjelang Bulan Ramadhan. Pelaksaan Mandi Belimau ini bertujuan untuk
membersihkan diri menjelang Bulan Ramadhan. Upacara diawali dengan
kegiatanNapak Tilas yaitu melakukan ziarah dan tabur bunga di makam Depati
Bunter, Desa Kimak yang ditempuh dengan menggunakan perahu motor untuk
menyeberang sungai. Setelah melakukan ziarah semua orang yang ikut kegiatan ini
pulang kembali dan menuju Dusun Limbung Desa Jada Bahrin untuk melakukan ritual
Mandi Belimau tersebut.
Mandi
Belimau adalah salah satu adat istiadat di Pulau Bangka Belitung yang diadakan
menjelang Bulan Ramadhan. Pelaksaan Mandi Belimau ini bertujuan untuk
membersihkan diri menjelang Bulan Ramadhan. Upacara diawali dengan
kegiatanNapak Tilas yaitu melakukan ziarah dan tabur bunga di makam Depati
Bunter, Desa Kimak yang ditempuh dengan menggunakan perahu motor untuk
menyeberang sungai. Setelah melakukan ziarah semua orang yang ikut kegiatan ini
pulang kembali dan menuju Dusun Limbung Desa Jada Bahrin untuk melakukan ritual
Mandi Belimau tersebut.Ritual Adat Mandi Belimau dimulai dengan Pengutaraan niat yang disertai doa yang dipimpin oleh Haji Ilyasak keturunan kelima dari Depati Bahrin yang sekarang adalah sebagai Pemuka Adat Kecamatan Merawang. Dalam Upacara ini Haji Ilsyak sebagai pemimpin menggunakan Kain Putih,sementara lima Pemuka Adat lainnya yang membantu menggunakan kain berwarna Hijau, Merah, Kuning, Hitam, dan Kelabu. Selanjutnya pelaksanaan mandinya dilakukan di depan Sungai Limbung, yang dimulai dengan membasahi telapak tangan dari kanan dan kiri, kemudian kaki kanan dan kiri yang diteruskan membasahi ubun-ubun dan seluruh anggota tubuh dengan siraman air yang dicampur dengan jeruk limau yang disimpan dalam gentong air.
Masyarakat
yang ingin dimandikan sebelumnya dianjurkan terlebih dahulu berdoa apa saja
untuk kebaikan mereka. Selain itu banyak masyarakat yang juga membawa pulang
air yang digunakan pada ritual Mandi Belimau ini karena mereka meyakini bahwa
air ini mempunyai khasiat tertentu.
Ritual adat Mandi Belimau ini adalah simbol-simbol tradisi yang baik untuk perenungan dan pensucian diri baik lahir maupun batin. Diharapkan simbol-simbol Mandi Belimau ini dapat membekas bagi masyarakat untuk kehidupan selanjutnya dan bukan hanya prosesi saja.
Ritual adat Mandi Belimau ini adalah simbol-simbol tradisi yang baik untuk perenungan dan pensucian diri baik lahir maupun batin. Diharapkan simbol-simbol Mandi Belimau ini dapat membekas bagi masyarakat untuk kehidupan selanjutnya dan bukan hanya prosesi saja.
Ruwah
Ruwah
merupakan arti dari kata ” arwah ” masyarakat bangka menyebutnya dengan bahasa
lokal sehari-hari dengan sebutan ruwah. Tradisi ruwah merupakan tradisi
mendoakan para arwah leluhur masyarakat setempat dipulau bangka, Selain sedekah
ruwah, ada beberapa ritual islami lain yang dilakukan masyarakat antara lain
lempar ketupat dan mandi belimau, perayaan ruwah tradisi adat budaya bangka.
Pelaksanaan
Acara sedekah ruwah dilakukan dibalai desa atau masjid dalam acara itu
masyarakat memanjat doa kepada Allah SWT serta junjungan nabi Muhammad SAW,
dalam perkumpulan sedekah ruwah dibalai desa masyarakat membawa makanan serta
masakan atau istilah masyarakat mneyebutnya nganggung setelah membaca doa-doa
barulah ketua pemimpin doa mempersilahkan memakan makanan serta masakan yang
telah dihidangkan.
Kongian
Namun
pada saat musim semi itu konon datang binatang buas yang disebut nian (ngian,
nyan) dari gunung atau laut untuk mengganggu manusia. Maka manusia mengenakan
pakaian warna merah dan membuat kebisingan dengan menyalakan petasan untuk
mengusir nian. Oleh karena itu Imlek disebut juga Kongian yang
berarti "mengusir/melewati nian". Di Indonesia sebutan kongian lebih
umum digunakan daripada kata Imlek atau Sin Cia di
daerah-daerah yang berpopulasi warga suku Hakka yang signifikan. Nian
dimanifestasikan dalam bentuk barongsai (samsi).
Sembahyang
Rebut
 Sembahyang Rebut (Chit Ngiat Pan) merupakan salah
satu warisan budaya Tionghoa yang jatuh pada bulan 7 tgl 15 kalender cina,
Sembahyang Rebut masih dilakukan hingga kini. Adat kepercayaan warga Tionghoa
mempercayai bahwa pada Chit Ngiat Pan pintu akherat terbuka lebar dimana
arwah-arwah yang berada di dalamnya keluar dan bergentayangan. Arwah-arwah
tersebut turun ke dunia ada yang pulang ke rumah keluarganya ada pula yang
turun dengan keadaan terlantar dan tidak terawat, sehingga para manusia
akan menyiapkan ritual khusus untuk diberikan kepada arwah yang terlantar
tersebut. Selain itu juga disediakan rumah-rumahan yang terbuat dari kertas,
uang dari kertas dan baju-baju dari kertas pula rumah-rumahan, uang dan
baju-baju tersebut yang memang diperuntukkan bagi para arwah.
Sembahyang Rebut (Chit Ngiat Pan) merupakan salah
satu warisan budaya Tionghoa yang jatuh pada bulan 7 tgl 15 kalender cina,
Sembahyang Rebut masih dilakukan hingga kini. Adat kepercayaan warga Tionghoa
mempercayai bahwa pada Chit Ngiat Pan pintu akherat terbuka lebar dimana
arwah-arwah yang berada di dalamnya keluar dan bergentayangan. Arwah-arwah
tersebut turun ke dunia ada yang pulang ke rumah keluarganya ada pula yang
turun dengan keadaan terlantar dan tidak terawat, sehingga para manusia
akan menyiapkan ritual khusus untuk diberikan kepada arwah yang terlantar
tersebut. Selain itu juga disediakan rumah-rumahan yang terbuat dari kertas,
uang dari kertas dan baju-baju dari kertas pula rumah-rumahan, uang dan
baju-baju tersebut yang memang diperuntukkan bagi para arwah.
Ritual
diadakan di kelenteng dimana puluhan umat memanjatkan panjatan doa keselamatan
dan keberkahannya. Selain dikunjungi oleh warga Tionghoa yang memang ingin
mengikuti ritual sembayang, juga datang warga lainnya yang memang sekedar ingin
menyaksikan ritual yang dipenuhi dengan nuansa mistis ini. Inilah salah satu
potret kerukunan umat beragama di Bangka Belitung. Sehari sebelum Sembahyang
Rebut, yaitu pada tgl 14-7 Kalender cina, warga Tionghoa melakukan ibadah
dirumah masing-masing untuk menghormati leluhur, Mereka mengirimkan dan
memanjatkan doa kepada leluhur dan orang tua yg telah meninggal. Ini sebagai
wujud bakti bahwa tak ada yang dapat memisahkan hubungan orang tua - anak -
cucu dan generasi berikutnya.
Kembali
ke tanggal 15 bulan 7, pada ritual acara ini, disediakan berbagai jamuan sesaji
yang tersusun rapi. Jamuan tersebut biasanya diletakkan diatas bangunan khusus
yang terbuat dari kayu dan papan. Terkadang dibuat dalam 2 tingkat. Terdapat
juga patung Dewa Akherat - Thai Se Ja yang dibuat dalam ukuran besar, serta
beberapa patung kecil lainnya. Thai S e Ja dipercaya bertugas utk mencatat
nama2 arwah yang akan berangkat beserta barang bawaan (sajian) yang dibawa.
Dari sore hingga malam, warga datang untuk bersembahyang sembari menunggu
ritual Chiong Si Ku (Perebutan).
Menjelang
tengah malam, jamuan-jamuan yang dihidangkan sudah dirasa cukup dinikmati oleh
para arwah, sehingga prosesi ritual dilanjutkan dengan upacara rebutan sesaji
yang berada di atas altar persembahan. Ada kepercayaan bahwa para peserta yang
ikut prosesi rebutan akan mendapatkan bala apabila tidak mendapatkan apa-apa.
Acara puncak dilakukan dengan pembakaran patung Thai Se Ja (sosok raksasa yang
sedang duduk dengan mata melotot). Acara puncak ini juga menandakan bahwa
arwah-arwah telah dibawa kembali oleh Thai Se Ja kembali ke dunia akherat.Pada hakekatnya,
ritual acara sembahyang rebut ini menurut adat kepercayaan warga Tionghoa
bertujuan untuk saling membantu.
Sembahyang
Kubur
 Upacara
ritual ziarah kubur untuk menghormati para leluhur yang dilaksanakan di
Perkuburan Kemujan Kota Sungailiat. Merupakan agenda tahunan Kalender Cina.
Sembahyang Kubur adalah tradisi masyarakal keturunan Tionghoa di Belitung untuk
bersembahyang di makam keluarga, pada musim sembanyang kubur ini biasanya
banyak orang Tionghoa Belitung di perantauan yang pulang ke Belitung unluk
melaksanakan tradisi ini.
Upacara
ritual ziarah kubur untuk menghormati para leluhur yang dilaksanakan di
Perkuburan Kemujan Kota Sungailiat. Merupakan agenda tahunan Kalender Cina.
Sembahyang Kubur adalah tradisi masyarakal keturunan Tionghoa di Belitung untuk
bersembahyang di makam keluarga, pada musim sembanyang kubur ini biasanya
banyak orang Tionghoa Belitung di perantauan yang pulang ke Belitung unluk
melaksanakan tradisi ini.
Kawin
Masal
Membaca
perkataan “Kawin Massal”, pastilah assosiasi kita akan tertuju kepada lebih
dari satu pasang muda mudi yang sedang melakukan akad nikah didepan seorang
penghulu. Sebenarnya bukanlah demikian makna yang terkandung didalam perkataan
“Kawin Massal” tersebut, melainkan waktu mengadakan malam pesta dari perkawinan
itulah yang dilaksanakan secara serempak pada hari dan malam yang telah
dimufakati bersama. Bulan-bulan September dan Oktober dari setiap tahun
merupakan bulan-bulan yang ramai dengan acara pesta Kawin Massal diseluruh
desa-desa, hanya pelaksanaan dari pesta Kawin Massal itu tidak serempak
(bersamaan) pada setiap desa. Ada pun penentuan hari dan tanggal tersebut
adalah berdasarkan musyawarah antara kepala-kepala desa dan para orangtua dari
masing-masing mempelai, agar hari dan tanggal waktu mengadakan pesta Kawin
Massal itu tidak jatuh bersamaan.
Setiap
Desa pada musim Kawin Massal saat ini, paling tidaknya akan mengadakan pesta
kawin massal sebanyak 5(lima) pasang mempelai, bahkan ada Desa yang sampai
menyelenggarakan 10(sepuluh) sampai 20(dua puluh) pasang, tergantung sedikit
banyaknya muda-mudi yang Kawin yang mempunyai keinginan yang sama untuk
merayakannya secara serempak.
Tradisi
Kawin Massal saat ini sudah cukup memperhatinkan karena beberapa desa sudah
jarang melaksanakannya dan baru-baru ini hanya tinggal satu Desa yang
melaksanakan pesta Kawin Massal yaitu Desa Serdang. Dalam hal ini Pemerintah
khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta masyarakat harus tetap
menjaga Tradisi Kawin Massal dalam upaya melestarikannya.
 Tradisi Kawin Massal sebenarnya hanyalah
dilaksanakan dengan acara-acara yang sederhana saja, seperti arak-arakan,
berkhatam Al-Qur’an, bergantian membaca do’a selamat dirumah para mempelai dan
paling banter memakai bunyi-bunyian berupa musik tiup (orang Jakarta
menyebutnya dengan musik tanjidor) atau sejenisnya, yang mencarter grup-grup
band dengan harga selangit itu, hanyalah acara tambahan diluar acara resmi atau
aslinya yang tak lebih dari suatu pemborosan. Kalau memang hal itu tidak bisa
ditinggalkan lagi, sepertinya akan lebih baik dan hemat jika mencarter satu
grup band saja untuk semua pasang mempelai dan semua pasang mempelai
dikumpulkan didalam satu bangsal yang besar, dan disediakan tempat-tempat duduk
untuk para undangan dan pengunjung dan disediakan juga hidangan-hidangan
sederhana. Hal tersebut dilakukan secara gotong royong antara orangtua
mempelai, dengan cara itu tidak ada pemborosan uang yang berlebihan, cara
inilah yang tepat disebut dengan pesta Kawin Massal.
Tradisi Kawin Massal sebenarnya hanyalah
dilaksanakan dengan acara-acara yang sederhana saja, seperti arak-arakan,
berkhatam Al-Qur’an, bergantian membaca do’a selamat dirumah para mempelai dan
paling banter memakai bunyi-bunyian berupa musik tiup (orang Jakarta
menyebutnya dengan musik tanjidor) atau sejenisnya, yang mencarter grup-grup
band dengan harga selangit itu, hanyalah acara tambahan diluar acara resmi atau
aslinya yang tak lebih dari suatu pemborosan. Kalau memang hal itu tidak bisa
ditinggalkan lagi, sepertinya akan lebih baik dan hemat jika mencarter satu
grup band saja untuk semua pasang mempelai dan semua pasang mempelai
dikumpulkan didalam satu bangsal yang besar, dan disediakan tempat-tempat duduk
untuk para undangan dan pengunjung dan disediakan juga hidangan-hidangan
sederhana. Hal tersebut dilakukan secara gotong royong antara orangtua
mempelai, dengan cara itu tidak ada pemborosan uang yang berlebihan, cara
inilah yang tepat disebut dengan pesta Kawin Massal.
Nganggung
Nganggung
adalah tradisi yang sudah dipraktekkan turun-terumurun oleh masyarakat Bangka
Belitung untuk merayakan hari-hari besar Islam. Uniknya tradisi ini juga tetap
berhahan meskipun di daerah perkotaan. Sebenarnya dimasa lalu nganggung ini
bukan hanya untuk perayaan hari besar Islam saja. Namun juga diadakan pada
acara pernikahan, do’a selamatan untuk arwah yang sudah meninggal, hingga
menyambut tamu kehormatan. Hanya saja yang tersisa sekarang adalah perayaan
nganggung pada saat hari besar Islam saja.
Beramai-ramai
Membawa Dulang ke Masjid
Pada
perayaan nganggung, masyarakat akan berkumpul di masjid terdekat di rumah
mereka sambil membawa berbagai hidangan makanan. Biasanya hidangan ini dibawa
menggunakan dulang tradisional yang terbuat dari semacam daun pandan. Pada
bagian luar dulang akan diberi cat. Dulang adalah bahasa Bangka Belitung untuk
tudung saji. Dulang inilah yang dimaksud dengan slogan kabupaten Bangka: Kota
Sepintu Sedulang. Apabila anda datang ke kampung-kampung pada saat perayaan,
maka dulang ini masih digunakan. Namun untuk perayaan nganggung di perkotaan,
biasanya diganti dengan nasi atau kue kotak yang dibawa dengan plastik besar.
Mungkin warga yang tinggal di daerah perkotaan tidak terlalu peduli dengan
detail tradisi atau mungkin juga dulang sulit dicari sehingga masyarakat
perkotaan menggantinya dengan kantong plastik besar. Sebenarnya tidak terlalu
masalah, hanya saja yang menjadi ciri khas nganggung adalah dulang ini.
Kain
Tradisional
Kain
Cual
Jika
Palembang terkenal dengan kain songket, Bangka juga memiliki kain khas bernama
kain cual. Kain yang menjadi kebanggaan masyarakat Bangka ini kini telah
menjadi seragam di beberapa Sekolah Dasar dan kantor-kantor pemerintahan di
daerah penghasil timah itu.
Asal
muasal kain cual sendiri berasal dari kain songket Palembang. Awal mula
perkembangan kain ini ada di Kota Muntok, Bangka, pada sekitar abad ke-17. Kain
cual pertama kali diperkenalkan oleh kakek buyut pendiri toko Kain Cual Ishadi
yang berada di Pangkal Pinang. Seiring berjalannya waktu, kain cual mulai
dikenal masyarakat sebagai kain khas Provinsi Bangka Belitung.
Kain
cual memiliki beberapa motif, seperti motif kembang gajah, bunga cina, naga
bertarung, dan burung hong. Beberapa motif kain cual ada yang dibuat dengan
menggunakan benang sutra dan bahkan ada yang dibuat dengan benang emas 18
karat.
Berkunjung
ke provinsi ini, dapat ditemukan beberapa toko yang khusus menjual kain cual.
Salah satunya adalah Toko Kain Cual Ishadi. Di toko yang terletak di Jalan
Ahmad Yani No. 46, Pangkalpinang, Bangka, ini, pengunjung dapat melihat-lihat
aneka jenis kain cual. Salah satu kain cual yang dipajang di sini konon sudah
berusia ratusan tahun. Kain ini merupakan milik kakek buyut sang pemilik toko,
yang juga memperkenalkan kain cual kepada masyarakat Bangka Belitung.
Alat
Musik dan Tarian Tradisional
Dambus
Tatkala
menikmati bunyi alunan musik Dambus yang didendangkan oleh para seniman, tentu
asyik untuk didengar dan dinikmati. Setiap lagu yang dinyanyikan selalu dalam
bentuk syair pantun.
Gendang
Melayu
 Sejenis gendang 'dua muka' yang berukuran besar dan
ditakrifkan sebagai Gendang Melayu. Ia mula berkembang di Negeri Kelantan dan
digunakan sebagai alat genderang dalam paluan untuk mengiringi teater
tradisional serta tarian klasik istana dan rakyat.
Sejenis gendang 'dua muka' yang berukuran besar dan
ditakrifkan sebagai Gendang Melayu. Ia mula berkembang di Negeri Kelantan dan
digunakan sebagai alat genderang dalam paluan untuk mengiringi teater
tradisional serta tarian klasik istana dan rakyat.
Rebana
Alat
musik Rebana asal usulnya berasal dari Jazirah Arab seperti halnya Rebab. Alat
musik Rebana sendiri biasanya digunakan dalam kesenian yang bernafaskan agama
Islam seperti hadrah ataupun saat membaca shalawat burdah.
Tari
Tanggai
Tari tanggai pada zaman dahulu
merupakan tari persembahan terhadap dewa siwa dengan membawa sesajian
yang berisi buah dan beranekan ragam bunga,karena ini berfungsi sebagai tari
persembahan pengantar sesajian maka tari tanggai pada zaman dahulu di
katagorikan tarian yang sakral. Di sebut tari tanggai karena setiap penarinya
menggunakan property tanggai di delapan jari (kecuali jempol).Tanggai tersebut
dari perak ataupun kuningan yang di pakai pada ujung jari tangan.
Tari
Tanggai sering dipergunakan dalam acara pernikahan masyarakat Sumatera Selatan,
acara-acara resmi organisasi dan pergelaran seni di sekolah-sekolah.
Sanggar-sanggar seni di kota Palembang banyak yang menyediakan jasa pergelaran
tarian tanggai ini, lengkap dengan kemewahan pakaian adat Sumatera Selatan.
Tari
Zapin
Zapin
masuk ke nusantara sejalan dengan berkembangnya agama Islam sejak abad ke
13 Masehi. Para pedagang dari Arab dan Gujarat yang datang bersama para ulama
dan senimannya, menelusuri pesisir nusantara. Di antara mereka ada yang tinggal
menetap di tempat yang diminati, dan ada pula yang kembali ke negeri mereka
setelah perdagangan mereka usai. Bagi yang menetap kemudian menikahi penduduk
setempat dan berketurunan hingga kini.
Zapin,
salah satu dari kesenian yang dibawa para pendatang tersebut kemudian
berkembang di kalangan masyarakat pemeluk agama Islam. Sekarang kita dapat
menemukan zapin hampir di seluruh pesisir
nusantara,
seperti: pesisir timur Sumatera Utara, Riau dan Kepulauannya, Jambi, Sumatera
Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jakarta, pesisir utara-timur dan
selatan Jawa, Nagara, Mataram, Sumbawa, Maumere, seluruh pesisir Kalimantan,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Ternate, dan Ambon. Sedangkan di
negara tetangga terdapat di Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura.
Di
nusantara, zapin dikenal dalam 2 jenis, yaitu zapin Arab yang mengalami
perubahan secara lamban, dan masih dipertahankan oleh masyarakat turunan Arab.
Jenis kedua adalah zapin Melayu yang ditumbuhkan oleh para ahli lokal, dan
disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya. Kalau zapin Arab hanya dikenal
satu gaya saja, maka zapin Melayu sangat beragam dalam gayanya. Begitu pula
sebutan untuk tari tersebut tergantung dari bahasa atau dialek lokal di mana
dia tumbuh dan berkembang. Sebutan zapin umumnya dijumpai di Sumatera Utara dan
Riau, sedangkan di Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu menyebutnya dana.
Julukan bedana terdapat di Lampung, sedangkan di Jawa umumnya menyebut zafin.
Masyarakat Kalimantan cenderung memberi nama jepin, di Sulawesi disebut jippeng,
dan di Maluku lebih akrab mengenal dengan nama jepen. Sementara di Nusatenggara
dikenal
dengan
julukan dana-dani.
Tari
Campak
Tari
Campak merupakan tarian dari daerah Bangka-Belitung yang menggambarkan
keceriaan bujang dan dayang di Kepulauan Bangka Belitung. Tarian ini biasanya
dibawakan setelah panen padi atau sepulang dari ume (kebun). Tarian ini berupa
pantun bersambut yang biasanya didendangkan oleh sepasang penari yang terdiri
dari laki-laki dan perempuan, dengan irama yang khas. Mereka menari diiringi
tabuhan gendang, biola dan gong yang ditabuh secara berkala. Para penari
menggunakan selembar saputangan yang dikibas-kibaskan mengiringi lenggok
gemulai sang penari. Pada saat tarian ini berlangsung biasanya penonton bebas
memberi sawer kepada “nduk campak” sebutan bagi penari perempuan pada tarian
ini. Sedangkan penari laki-laki disebut “penandak”.
Budaya Eropa membawa pengaruh terhadap Tarian Campak
ini dan dapat dilihat dari alat musik pengiringnya yaitu akordion. Pengaruh ini
tampak juga pada busana modern Eropa yang dipakai penari perempuannya, seperti
gaun panjang, topi, dan sepatu berhak tinggi. Sedangkan penari laki-laki
mengenakan busana tradisional yakni kemeja, celana panjang, peci, dan
selendang. Walaupun mendapat pengaruh dari budaya Eropa, tari campak Bangka
Belitung tetap merupakan tari tradisional karena memiliki nilai-nilai budaya
lokal yang dipertahankan. Tari campak biasanya dibawakan untuk merayakan waktu
musim panen padi. Selain itu tari yang penuh keceriaan sering dibawakan para
muda mudi sepulangnya dari ume atau kebun. Dalam perkembangannya Tari
Campak juga dipertunjukan dalam pesta-pesta adat seperti penyambutan tamu
dan pernikahan.
Pagelaran
tari campak selalu meriah dan menarik hati. Para penari tidak hanya menari
berpasang-pasangan mengikuti irama musik, mereka juga melantunkan pantun.
Mereka saling berbalas pantun sampai akhirnya penari laki-laki merasa kalah.
Uniknya, setelah kalah membalas pantun penari laki-laki harus memberikan uang
kepada penari perempuan. Kemeriahan gerak tari dan lantunan pantun yang
dibawakan oleh para penari tari campak diiringi oleh alat musik tradisional
seperti gong dan gendang serta alat musik modern Eropa yaitu akordion dan
biola.
Rudat
Rudat
merupakan perpaduan Seni Tari dan Seni Suara. Tarian Rudat biasanya disajikan
dalam acara Adat Lampung. Para penari menggunakan seragam / Pakaian Adat
Lampung. Sambil menari, mereka melantunkan syair-syair, diiringi oleh tabuhan
Rebana, yang disesuiakan dengan syairnya. Biasanya selain Rudat, dalam suatu
rombongan arak-arakan, ada juga yang menyuguhkan Pencak Silat, dan Tuping.
Dalam
Rudat dipilih Seseorang yang dipercaya sebagai ketua Rudat. tarian Rudat
biasanya dibawakan dibeberapa desa di Lampung, tarian Rudat ini masih sering
dan bisa kita nikmati bila ada acara Adat Pernikahan, Khitan dan Acara Adat
Lainnya bahkan beberapa kali dipertunjukan pada saat acara nasional.
Tari
Bahtera Bertiang Tujuh
Tarian
"Bahtera Bertiang Tujuh" yang ditampilkan oleh Sanggar "Pesona
Wangka" Sungai Liat Bangka itu settingnya dimulai sejak abad ke 12 saat
kapal layar dengan tujuh tiang mengarungi Samudera.
Selanjutnya dikisahkan dalam tarian bagaimana Pulau Bangka yang kaya dengan timah mulai didatangi berbagai orang untuk ikut menikmati hasil timahnya. Masuknya penjajah, perlawanan dari rakyat Bangka, hingga jaman reformasi
Selanjutnya dikisahkan dalam tarian bagaimana Pulau Bangka yang kaya dengan timah mulai didatangi berbagai orang untuk ikut menikmati hasil timahnya. Masuknya penjajah, perlawanan dari rakyat Bangka, hingga jaman reformasi
Sekapur
Sirih
Gerakan-gerakan
lincah penari yang bergerak ke kanan dan kiri diiringi musik tradisional gambus
khas Belitung membuat tarian ini begitu rancak. Gerakan penari seakan-akan
memberikan isyarat selamat datang kepada para tamu.
Tari
sekapur sirih biasa ditarikan 10 sampai 12 penari. Diantara para penari ini
biasanya terdapat dua penari laki-laki yang berposisi di belakang. Tari sekapur
sirih menjadi tarian yang ditampilkan dalam perhelatan besar di Belitung.
Sebagai tarian selamat datang, biasanya tari sekapur sirih ini mendapatkan
perhatian dan sambutan meriah dari para tamu undangan yang hadir.
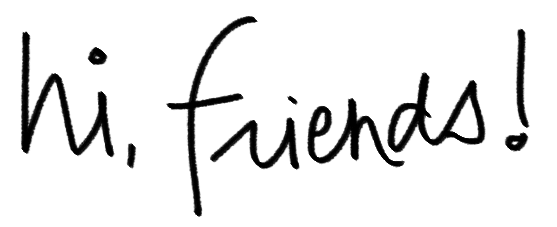


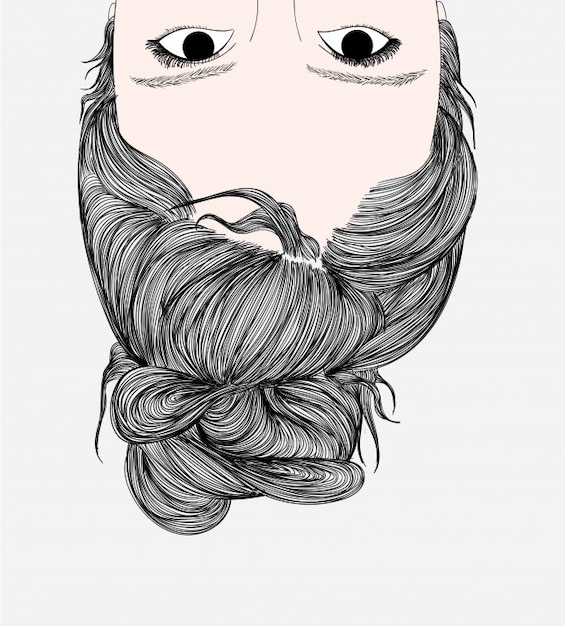

0 komentar